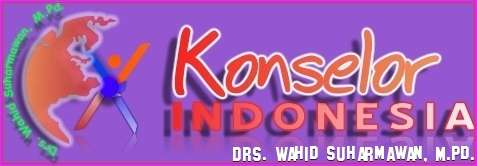BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam layanan bimbingan konseling terdapat landasan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Landasan ini berfungi sebagai fondasi dalam layanan bimbingan konseling, seperti sebuah bangunan yang memiliki fondasi agar berdiri tegak dan kokoh.
Terdapat lima landasan, dan diantaranya adalah landasan sosial budaya yang membahas pengaruh sosial budaya terhadap individu, hambatan-hambatan komunikasi dan penyesuaian diri sebagai dampak perbedaan antar budaya serta pengaruh perbedaan antar budaya itu terhadap layanan bimbingan dan konseling.
Maka dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pemahaman seorang konselor terhadap pendidikan sosial dan budaya yang erat hubungannya dengan landasan sosial budaya yang terdapat dalam layanan bimbingan koseling itu sendiri.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari pendidikan budaya?
2. Bagaimana bentuk budaya yang ada di sekolah?
3. Bagaimana pemahaman individu terhadap nilai norma sosial?
4. Bagaimana pemahaman seorang konselor terhadap nilai norma sosial?
C. Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemahaman seorang konselor terhadap pendidikan sosial dan budaya.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pendidikan Budaya
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Kelakuan manusia pada hakekatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Hubungan antara individu itu bukan sepihak, melainkan timbal balik. Kebudayaan mempengaruhi individu dengan berbagai cara, akan tetapi individu juga mempengaruhi kebudayaan sehingga terjadi perubahan sosial. Latihan yang diterima oleh anggota baru tentang cara-cara hidup suatu masyarakat berkat interaksi dengan lingkungannya disebut pengaruh kebudayaan atas individu.
Kebudayaan dipandang sebagai cara-cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Ada masalah yang universal seperti memenuhi kebutuhan biologis. Namun tiap masyarakat memilih cara yang dianggap paling sesuai sehingga tidak ada dua masyarakat yang sama kebudayaannya.
Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu dikemukakan pengertian istilah budaya, karakter bangsa, dan pendidikan.
Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam ligkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.
Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.
Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah; oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.
B. Budaya yang ada di Sekolah
Sistem pendidikan mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari murid-murid. Kehidupan di sekolah serta norma-norma yang berlaku dapat disebut kebudayaan sekolah. Walaupun kebudayaan sekolah merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat luas, namun mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai sesuatu “sub-culture”. Sekolah bertugas untuk menyampaikan kebudayaan kepada generasi baru dan karena itu harus selalu memperhatikan masyarakat dan kebudayaan umum. Akan tetapi di sekolah itu sendiri timbul pola-pola kelakuan tertentu. Ini mungkin karena sekolah mempunyai kedudukan yang agak terpisah dari arus umum kebudayaan.
Dalam sub-kebudayaan sekolah juga terjadi oleh sebab sebagian yang cukup besar dari waktu murid terpisah dari kehidupan orang dewasa. Dalam situasi ini dapat berkembang pola kelakuan khas anak muda yang tampak dari pakaian, bahasa, kebiasaan serta upacara-upacara. Sebab lain timbulnya kebudayaan sekolah ialah tugas sekolah yang khas yakni mendidik anak dengan menyampaikan sejumlah pengetahuan, sikap, keterampilan yang sesuai dengan kurikulum dengan metode dan teknik kontrol tertentu yang berlaku di sekolah itu.
Dalam melaksanakan kurikulum berkembang sejumlah pola kelakuan yang khas bagi sekolah yang berbeda dengan yang terdapat pada kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Tiap kebudayaan mengandung bentuk kelakuan yang diharapkan dari anggotanya. Di sekolah diharapkan bentuk kelakuan tertentu dari semua murid dan guru. Itulah yang menjadi norma bagi setiap murid dan guru. Norma ini nyata dalam interaksi guru dan murid, dalam peraturan-peraturan sekolah, dalam tindakan dan hukuman terhadap pelanggaran, juga dalam berbagai kegiatan seperti upacara-upacara. Jadi budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Adapun nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air
Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komuniktif
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Sebuah budaya sekolah yang berlangsung di sebuah sekolah bisa saja diterapkan di sekolah lain, sebaliknya tidak semua hal yang menjadi budaya di sebuah sekolah bisa diaplikasikan disekolah lain. Sebuah budaya sekolah yang bisa dirasakan oleh individu yang ada didalamnya akan menjelma menjadi iklim sekolah yang melingkupi dan menjadi dasar pijakan pengembangan sekolah.
C. Pemahaman Individu Terhadap Nilai Norma Sosial
1. Nilai Sosial
Satu bagian penting dari kebudayaan atau suatu masyarakat adalah nilai sosial. Suatu tindakan dianggap sah, dalam arti secara moral diterima, kalau tindakan tersebut harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan. Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kasalehan beribadah, maka apabila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjingan, cercaan, celaan, cemoohan, atau bahkan makian. Sebaliknya, kepada orang-orang yang rajin beribadah, dermawan, dan seterusnya, akan dinilai sebagai orang yang pantas, layak, atau bahkan harus dihormati dan diteladani.
Dalam Kamus Sosiologi yang disusun oleh Soerjono Soekanto disebutkan bahwa nilai (value) adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Horton dan Hunt (1987) menyatakan bahwa nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti apa tidak berarti. Dalam rumusan lain, nilai merupakan anggapan terhadap sesuatu hal, apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, penting atau tidak penting, mulia ataukah hina. Sesuatu itu dapat berupa benda, orang, tindakan, pengalaman, dan seterusnya.
Prof. Notonegoro membedakan nilai menjadi tiga macam, yaitu:
(1) Nilai material, yakni meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia,
(2) Nilai vital, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas, dan
(3) Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia: nilai kebenaran, yakni yang bersumber pada akal manusia (cipta), nilai keindahan, yakni yang bersumber pada unsur perasaan (estetika), nilai moral, yakni yang bersumber pada unsur kehendak (karsa), dan nilai keagamaan (religiusitas), yakni nilai yang bersumber pada revelasi (wahyu) dari Tuhan.
Seorang individu mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda, bahkan bertentangan dengan individu-individu lain dalam masyarakatnya. Nilai yang dianut oleh seorang individu dan berbeda dengan nilai yang dianut oleh sebagaian besar anggota masyarakat dapat disebut sebagai nilai individual. Sedangkan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut nilai sosial.
2. Norma sosial
Kalau nilai merupakan pandangan tentang baik-buruknya sesuatu, maka norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima karena sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat ataukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Norma dibangun di atas nilai sosial, dan norma sosial diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Pelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi dari masyarakat.
Dilihat dari tingkat sanksi atau kekuatan mengikatnya terdapat macam-macam norma sosial,diantaranya :
1. Tata cara atau usage. Tata cara (usage); merupakan norma dengan sanksi yang sangat ringat terhadap pelanggarnya, misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum. Pelanggaran atas norma ini hanya dinyatakan tidak sopan.
2. Kebiasaan (folkways). Kebiasaan (folkways); merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Misalnya mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, dst.
3. Tata kelakuan (mores). Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran agama atau ideology yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya disebut jahat. Contoh: larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan napza, mencuri, dst.
4. Adat (customs). Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat, apabila adat menjadi tertulis ia menjadi hukum adat.
5. Hukum (law). Hukum merupakan norma berupa aturan tertulis, ketentuan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar dirumuskan secara tegas. Berbeda dengan norma-norma yang lain, pelaksanaan norma hukum didukung oleh adanya aparat, sehingga memungkinkan pelaksanaan yang tegas.
Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan ataupun tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Di wilayah perdesaan, sejak berbagai siaran dan tayangan telivisi swasta mulai dikenal, perlahan-lahan terlihat bahwa di dalam masyarakat itu mulai terjadi pergesaran nilai, misalnya tentang kesopanan. Tayangan-tayangan yang didominasi oleh sinetron-sinetron mutakhir yang acapkali memperlihatkan artis-artis yang berpakaian relatif terbuka, sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat menjadi semakin longgar. Berbagai kalangan semakin permisif terhadap kaum remaja yang pada mulanya berpakaian normal, menjadi ikut latah berpakaian minim dan terkesan makin berani. Model rambut panjang kehitaman yang dulu menjadi kebanggaan gadis-gadis desa, mungkin sekarang telah dianggap sebagai simbol ketertinggalan. Sebagai gantinya, yang sekarang dianggap trendy dan sesuai dengan konteks zaman sekarang (modern) adalah model rambut pendek dengan warna pirang atau kocoklat-coklatan. Jadi berubahnya nilai akan berpengaruh terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
D. Pemahaman Seorang Konselor Terhadap Nilai Norma Sosial
Mengacu pada landasan sosial budaya yang terdapat pada layanan bimbingan konseling, konselor seharusnya memahami arti penting akan nilai dan norma sosial yang terkandung dalam sebuah kebudayaan. Kita dilahirkan memiliki kebudayaan, dan kebudayaan setiap orang tidak semuanya sama. MC Daniel memandang setiap anak, sejak lahirnya harus memenuhi tidak hanya tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya ditempat ia hidup, tuntutan budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. Jadi, bimbingan konseling harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam pelayanannya agar menghasilkan pelayanan yang lebih efektif. Karena perbedaan dalam latar belakang ras atau etnik, kelas sosial ekonomi dan pola bahasa dapat menimbulkan masalah dalam hubungan konseling.
Landasan sosial-budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial-budaya dimana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial- budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial-budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial-budaya yang melatarbelakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak “dijembatani”, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang besangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.
Dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien, yang mungkin antara konselor dan klien memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Pederson dalam Prayitno (2003) mengemukakan lima macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuain diri antar budaya, yaitu :
(a) perbedaan bahasa;
(b) komunikasi non-verbal;
(c) stereotipe;
(d) kecenderungan menilai; dan
(e) kecemasan.
Kurangnya penguasaan bahasa yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa non-verbal pun sering kali memiliki makna yang berbeda-beda, dan bahkan mungkin bertolak belakang. Stereotipe cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subyektif (social prejudice) yang biasanya tidak tepat. Penilaian terhadap orang lain disamping dapat menghasilkan penilaian positif tetapi tidak sedikit pula menimbulkan reaksi-reaksi negatif. Kecemasan muncul ketika seorang individu memasuki lingkungan budaya lain yang unsur-unsurnya dirasakan asing. Kecemasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya dapat menuju ke culture shock, yang menyebabkan dia tidak tahu sama sekali apa, dimana dan kapan harus berbuat sesuatu. Agar komuniskasi sosial antara konselor dengan klien dapat terjalin harmonis, maka kelima hambatan komunikasi tersebut perlu diantisipasi.
Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Moh. Surya (2006) mengetengahkan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat bhinneka tunggal ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pendidikan budaya diartikan sebagai suatu usaha secara sadar dan sistematis untuk menegmbangkan potensi/kemampuan peserta didik dalam keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan.
Untuk itu sekolah atau seluruh warga sekolah diharapkan menerapkan kebudayaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Itulah yang menjadi norma bagi setiap murid dan guru. Norma ini nyata dalam interaksi guru dan murid, dalam peraturan-peraturan sekolah, dalam tindakan dan hukuman terhadap pelanggaran, juga dalam berbagai kegiatan seperti upacara-upacara.
Sementara konselor menjadikan kebudayaan sebagai landasan/acuan dalam menjalankan layanan bimbingan konseling.
B. Saran
Demikian makalah kami mengenai “Pemahaman Konselor Terhadap Pendidikan, Sosial dan Budaya”. Semoga makalah yang kami buat ini bermanfaat bagi para pembaca. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penulisan, untuk itu kami mohon kritik dan saran yang dapat membangun kami. Sehingga pada makalah yang berikutnya bisa lebih baik dari sekarang. Akhir kata, kami ucapakan terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
1. S, Nasution. Sosiologi Pendidikan. 1983. Bandung
2. Ramon, Sumarsi. Sosiologi dan Antropologi. 1985. Surabaya
4. http://agsasman3yk.wordpress.com/2009/09/01/nilai-dan-norma-sosial/